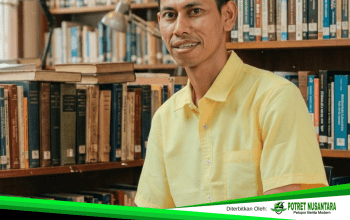Oleh: Muhammad Yasin (Ketua HMI Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Delapan dekade sudah Indonesia mengaku merdeka. Tapi kita masih berdiri tegak di depan tiang bendera, bukan di hadapan keadilan. Lagu kebangsaan dinyanyikan, tapi nadanya lebih nyaring dari maknanya. Upacara digelar, tapi substansi kemerdekaan lebih sering tertinggal di ruang transit kekuasaan, tak pernah sampai ke pelosok dusun tempat rakyat menggantung harapan dengan benang yang nyaris putus.
Di istana, para pemegang mandat sibuk membacakan angka. Pertumbuhan ekonomi, katanya, stabil di angka 5,12 persen. Tentu, angka itu terasa manis bagi mereka yang menyesapnya dari ruang rapat berpendingin udara. Tapi cobalah tengok keluar dari jendela kekuasaan, dan tanya pada tukang parkir yang dikejar e-wallet, buruh harian yang dilindas otomatisasi, atau mahasiswa yang ijazahnya kini hanya berlaku sebagai pelengkap folder lamaran kerja yang tak pernah dibaca.
Ada yang lebih absurd dari kemiskinan, yaitu kosmetika negara yang berusaha menutupi bau busuknya. Program makan siang gratis, misalnya, dipoles menjadi narasi penyelamat generasi. US$28 miliar dihamburkan demi nasi kotak, sementara sektor pendidikan dan kesehatan dicukupi dengan retorika. Negeri ini sedang belajar satu hal penting: bahwa lapar bisa ditambal dengan logistik, tapi kebodohan adalah proyek jangka panjang.
Sementara itu, ketimpangan ekonomi tetap berdiri kokoh seperti tugu peresmian. Gini Rasio stagnan di angka 0,379, seolah berkata: “Kami konsisten mempertahankan jurang.” Yang kaya kian kaya karena punya akses ke pengambilan keputusan. Yang miskin tetap miskin karena hanya diberi akses ke panggung upacara. Anak muda yang dulu digadang-gadang sebagai lokomotif bangsa, kini justru dijejali utang pendidikan dan janji palsu industrialisasi. NEET- mereka yang tak sekolah, tak kerja, dan tak ikut pelatihan kian banyak, dan negara memilih menutup statistiknya dengan dalih “transisi demografi”.
Di halaman depan konstitusi, tertulis “kedaulatan di tangan rakyat”. Tapi di belakang layar kekuasaan, hukum dikelola seperti promosi di pusat perbelanjaan: siapa yang punya kupon, dia dapat diskon. Revisi Undang-Undang TNI membuka jalan bagi militer untuk kembali masuk ke urusan sipil, seperti hantu reformasi yang enggan istirahat. KUHP baru membawa pasal penghinaan terhadap presiden kembali hidup, seperti mantan yang tak pernah move on. Demokrasi dipertahankan, tapi seperti bonsai: dirawat agar tetap kecil dan indah, tak pernah besar dan membesar.
Sementara itu, aktivisme dijinakkan dengan dua alat: pasal dan pasukan. Data dari Human Rights Watch mencatat ratusan demonstran ditangkap, sebagian dibungkam secara digital, sisanya diserahkan kepada algoritma untuk dikubur dalam ketidakterlihatan. Rezim ini tampaknya belajar satu hal penting: bahwa menghapus kritik lebih efisien daripada menjawabnya.
Lingkungan hidup? Tema yang bagus untuk seminar dan kampanye, tapi buruk untuk praktik dan niat. Pemerintah menyita dua juta hektare lahan sawit ilegal, lalu menyerahkannya ke BUMN, bukan ke petani atau masyarakat adat. Di Latimojong, tambang emas beroperasi mulus, menambang lebih banyak luka daripada emas. Seolah kita sedang menyaksikan kolonialisme dengan seragam baru dan bendera yang sama.
Namun, seperti bara di tengah reruntuhan, masih ada perlawanan. Mahasiswa turun ke jalan dalam aksi “Indonesia Gelap”. Mereka tidak menuntut nasi bungkus, tapi nalar. Mereka tahu, dalam republik yang gemar mengemas propaganda sebagai prestasi, diam adalah bentuk kolaborasi. Dalam sejarah bangsa ini, perubahan tidak lahir dari pidato seremonial, tapi dari kerikil-kerikil kecil yang dilemparkan ke jendela kekuasaan.
Kemerdekaan, jika hanya dirayakan tanpa dipertanyakan, hanyalah ilusi kolektif. Sebuah pesta yang digelar setiap tahun untuk meninabobokan rakyat dari kenyataan bahwa yang merdeka hanyalah simbol, bukan sistem. Mahasiswa bukan hanya anak kuliah yang sedang mencari SKS, tapi suara nalar publik yang tak punya ruang di parlemen.
17 Agustus bukan sekadar momen untuk mengenakan batik terbaik dan selfie di depan gapura merah-putih. Ia harus menjadi titik perenungan: apakah kita benar-benar merdeka, atau hanya sedang menyewa panggung untuk menutupi pangkal luka?
Dirgahayu Republik Indonesia. Jangan buru-buru bangga. Karena tugas kita bukan hanya menjaga bendera tetap berkibar, tapi memastikan akal sehat tidak terus disekap di ruang tunggu kekuasaan.