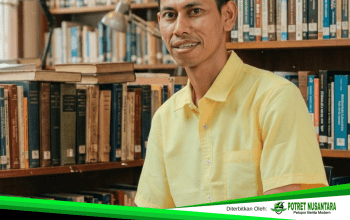Penulis: Iwan Mazkrib (Seniman Hukum)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Dalam pusaran sejarah manusia yang penuh riuh dan retak, selalu ada tegangan antara yang hadir dan yang akan datang, antara yang nyata dan yang dijanjikan, antara dunia kini dan dunia akhir. Inilah wilayah kontemplatif dari Paradoks Imanensi Eschatos, sebuah dialektika antara kehadiran transendental yang merasuk ke dalam realitas sosial (imanensi), dan janji final tentang pemenuhan nilai-nilai ilahi dalam horizon eschatos, hari penghabisan.
Paradoks ini bukan semata teka-teki teologis, melainkan denyut terdalam dari keresahan sosial manusia modern; mengapa dunia yang katanya dikuasai oleh nilai-nilai ketuhanan justru memproduksi luka-luka sosial yang tak kunjung sembuh?
Di tengah derasnya pembangunan fisik, globalisasi teknologi, dan narasi kemajuan, masyarakat hari ini justru terperangkap dalam keterasingan eksistensial dan ketimpangan struktural. Keadilan seakan hadir dalam retorika, terkadang ghaib dalam praktik; kebenaran bersinar dalam doktrin, tapi redup dalam kebijakan.
Paradoks Imanensi Eschatos menyingkap kenyataan ini, bahwa ketika manusia mengklaim Tuhan hadir di tengah masyarakat, dalam hukum, moral, bahkan birokrasi. Namun gagal menghadirkan nilai hak asasi, keadilan, dan pembebasan, maka imanensi itu menjadi semu. Yang transenden telah dijadikan alat kekuasaan.
Namun di sisi lain, paradoks ini juga menyimpan kekuatan: eschatos, janji tentang tatanan akhir yang adil, bukanlah sekadar masa depan yang menunggu, melainkan panggilan untuk bertindak di sini dan saat ini. Imanensi bukan ketundukan pasrah pada yang ada, melainkan kekuatan kreatif untuk melawan ketimpangan sosial sebagai wujud dari iman kepada keadilan ilahi yang akan datang.
Paradoks ini mengajak kita berpikir ulang: Bahwa yang ilahi tidak hanya berada di surga yang jauh di kemudian hari, tetapi sedang berteriak dalam kelaparan si miskin, dalam tangisan korban ketidakadilan, dalam do’a yang sunyi di lorong gelap perkampungan. Dan eschatos, bukan sekadar kiamat dalam pengertian kosmis, tetapi juga revolusi kesadaran, ketika masyarakat bangkit menuntut haknya, menolak penindasan, dan merindukan dunia yang lebih adil dan bermakna.
Paradoks Imanensi Eschatos bukanlah paradoks yang membelenggu, melainkan dialektika yang membebaskan. Ia menyentak kita agar jangan puas dengan tatanan sosial yang timpang, walau dibungkus dalil suci. Ia mengajak kita menghadirkan Tuhan bukan dalam simbol, tetapi dalam keberpihakan nyata kepada yang terpinggirkan. Dengan demikian, iman tidak lagi menjadi pelarian dari dunia, tetapi kekuatan untuk menebus dunia. Dan eschatos, bukan akhir dari sejarah, melainkan awal dari tanggung jawab sosial kita yang sejati.
Dalam etos kekuasaan di antara kejumudan Hukum dan HAM. Paradoks imanensi eschatos menjadi semacam “kehampaan kehadiran”: kekuasaan yang hadir dalam segala bentuknya, namun tidak menghadirkan makna. Ia kehilangan rujukan transenden keadilan, kebenaran, martabat manusia, yang semestinya menjadi arah setiap bentuk hukum dan pemerintahan. Etos kekuasaan yang eskatologis adalah kesadaran bahwa kekuasaan bersifat sementara, namun dampaknya kekal bagi nasib manusia. Bahwa hukum dan HAM bukan instrumen formal, melainkan komitmen etis yang mesti terus-menerus direfleksikan dan diperjuangkan.
Paradoks Imanensi Eschatos bukan sekadar kontradiksi intelektual, tapi refleksi terdalam dari kegagalan peradaban menghargai hakikat manusia.
Demikian jeritan sunyi dari Paradoks Imanensi Eschatos, sebuah simpul intelektual yang menegaskan kontradiksi antara klaim kehadiran ilahiah dalam struktur dunia (imanensi), dan janji pemulihan total dalam horizon sejarah akhir (eschatos), yang kini bersinggungan tajam dengan kejumudan Hak Asasi Manusia (HAM).
HAM lahir sebagai puncak kesadaran modern atas martabat manusia yang tak dapat dilenyapkan oleh kuasa raja, negara, maupun ideologi. Namun kini, dalam geliat globalisasi dan represi terselubung, HAM justru menjadi artefak normatif yang beku dan hanya dikagumi, tetapi tak diperjuangkan; ditulis, tetapi tak ditegakkan.
Di sinilah letak paradoksnya. Bahwa kita hidup dalam dunia yang terus-menerus mengklaim nilai-nilai universal/iman kepada Tuhan, penghormatan atas manusia, keadilan sebagai prinsip kosmis, namun praktik sosial dan politik kian menjauh dari cita-cita tersebut. Negara mengakui HAM dalam konstitusi, tapi patah dalam praktik. Kekuasaan hanya berwujud Validasi Fun-teck, terlihat dari kondisi kebatinan bangsa.
Paradoks Imanensi Eschatos menunjukkan bahwa imanensi Tuhan yang semestinya melahirkan etika pembebasan, justru terkooptasi menjadi legitimasi kuasa. Eschatos, janji keselamatan dan keadilan final, direduksi menjadi penantian fatalistik, bukan motivasi transformatif. Maka HAM pun ikut terjebak dalam pusaran ini, dijadikan jargon tanpa jiwa, dijalankan tanpa nurani.
Dalam ruang ini, kejumudan HAM bukan hanya stagnasi hukum, tetapi stagnasi moral kolektif. Ketika pelanggaran HAM dianggap normal, ketika pembungkaman dianggap stabilitas, ketika suara korban diabaikan atas nama “ketertiban umum”, maka sesungguhnya kita sedang membunuh eschatos itu sendiri.
HAM menjadi beku ketika ia dipisahkan dari ketegangan antara imanensi dan eschatos. HAM kehilangan daya saat ia diputus dari harapan eskatologis tentang dunia yang benar-benar adil. Sebab HAM bukan hanya hak-hak formal, melainkan pancaran dari keyakinan bahwa manusia, betapapun rentannya, adalah refleksi dari sesuatu yang ilahi, yang harus dilindungi bukan karena kuat, tetapi karena lemah.
Untuk menembus kejumudan HAM, kita harus memulihkan ketegangan kreatif antara imanensi dan eschatos. Kita harus hadirkan kembali nilai-nilai transenden ke dalam ruang sosial, bukan sebagai dogma kekuasaan, tetapi sebagai energi pembebasan. Bahwa janji eschatos harus menjadi visi politik sehari-hari, bukan sekadar utopia akhir zaman.
Dalam dunia yang kian dingin oleh legalisme dan nihilisme moral, Paradoks Imanensi Eschatos adalah panggilan untuk membumikan yang suci dan meninggikan yang manusiawi. Di sinilah letak revolusi peradaban, ketika kita tidak sekadar menyebut Tuhan, tetapi menghidupkan keadilan-Nya dalam perlakuan kita terhadap sesama “Pengakuan martabat manusia secara tak bersyarat”.
Kekuasaan menata realitas sosial seperti arsitek yang dingin: terukur, terkendali, namun sunyi dari nurani. Di sinilah paradoks itu menggema: “jalan menuju yang seharusnya”, melainkan hanya pembenaran atas status quo. HAM berubah menjadi jargon administratif, dinyatakan dalam piagam, namun dikhianati dalam praktik.
Paradoks imanensi eschatos bukan kutukan. Ia adalah cermin bahwa peradaban kita butuh pembaruan terus-menerus, bahwa kekuasaan harus terus dihadapkan pada cita ideal. Demikian pula hukum dan HAM bukan sekedar instrumen formal, melainkan komitmen etis yang mesti terus-menerus direfleksikan dan diperjuangkan, sebagai bahagian dari iman etis kolektif umat dan bangsa, menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Semesta Alam.