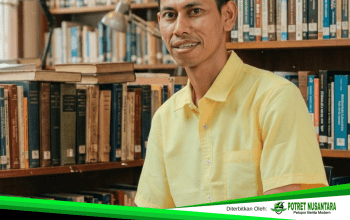Oleh: Aa Muhamad Zaenudin, S.A.P, S.H., M.H.
(Ketua LBH GP Ansor Kota Bekasi)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Apakah Kebijakan Pembagian Kuota Haji Khusus Tahun 2024 Melanggar Hukum?
Isu pertama yang perlu dijawab adalah; Apakah kebijakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam membagi kuota Haji tambahan tahun 2024 dengan komposisi 50 persen Haji reguler dan 50 persen Haji khusus merupakan perbuatan yang melanggar hukum?
Untuk menjawabnya, analisis harus dimulai dari kerangka normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan Haji Nasional.
Undang-undang tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8, termasuk membedakan antara “kuota Haji reguler dan Haji khusus”.
Namun demikian, Undang-undang yang sama juga mengatur kondisi khusus berupa penambahan kuota Haji setelah kuota pokok ditetapkan. Pasal 9 ayat (1) UU Haji memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk menetapkan kuota haji tambahan, sedangkan ayat (2) menyerahkan mekanisme pengisiannya kepada pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.
Secara sistematik, norma ini berdiri sendiri dan tidak secara eksplisit mengaitkan kuota tambahan dengan batasan kuota Haji khusus sebesar 8 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 64. Oleh karena itu, menarik Pasal 64 secara otomatis untuk membatasi kuota tambahan merupakan penafsiran yang lemah secara metodologis dan mengabaikan karakter eksepsional kuota tambahan itu sendiri.
Kebijakan pembagian kuota Haji tambahan tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 H/2024 M tidak dapat dilepaskan dari konteks faktual dan teknis penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun berjalan.
Kebijakan tersebut lahir dalam kerangka adanya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yang disusun berdasarkan hasil simulasi teknis bersama, khususnya terkait penerapan kebijakan zonasi Mina serta keterbatasan kapasitas penempatan jemaah.
Kondisi faktual menunjukkan bahwa kapasitas Mina telah berada dalam tingkat kepadatan yang sangat tinggi bahkan sebelum adanya penambahan kuota, sehingga setiap kebijakan penambahan Jemaah harus mempertimbangkan aspek Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan Jemaah secara serius.
Pertimbangan tersebut sejalan dengan asas penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang menekankan prinsip Kemaslahatan, Keselamatan, Keamanan, Profesionalitas, dan Akuntabilitas.
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kebijakan pembagian kuota Haji tambahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk diskresi administratif yang sah, karena diambil dalam rangka menjamin kepentingan umum serta mencegah timbulnya risiko yang lebih besar apabila kuota tambahan sepenuhnya dialokasikan tanpa mempertimbangkan keterbatasan teknis di lapangan.
Oleh karena itu, secara hukum administrasi, kebijakan pembagian kuota Haji tambahan tahun 2024 tidak dapat serta-merta dinilai sebagai kebijakan yang melanggar hukum.
Apabila isu hukum utama berangkat dari anggapan bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 mengandung cacat hukum, maka pengujiannya harus dilakukan dalam kerangka Hukum Administrasi Negara.
Penilaian tersebut mencakup pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan dimaksud, termasuk apakah keputusan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Tanpa melalui pengujian administratif tersebut, pelabelan kebijakan sebagai perbuatan melawan hukum menjadi prematur dan berpotensi mengaburkan batas antara kesalahan Administrasi dan pertanggungjawaban Pidana.
Apakah Kebijakan Pembagian Kuota Haji Tambahan Tahun 2024 Merugikan Keuangan Negara?
Isu kedua berkaitan dengan dugaan bahwa kebijakan pembagian kuota Haji tambahan tahun 2024 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara. Dalam konteks Hukum Pidana, khususnya Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan secara nyata dan terukur.
Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat merugikan keuangan negara” tidak lagi dapat ditafsirkan sebagai potensi kerugian, melainkan harus dimaknai sebagai kerugian aktual yang benar-benar telah terjadi.
Dalam perkara kuota Haji 2024, hingga penetapan tersangka terhadap Yaqut Cholil Qoumas, kerugian Negara masih berada dalam tahap perhitungan dan estimasi, serta belum ditetapkan secara final oleh Lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan.
Tanpa adanya hasil audit yang final dan mengikat, unsur kerugian keuangan Negara secara hukum belum terpenuhi. Dalam Hukum Pidana, ketidakpastian terhadap unsur delik tidak dapat ditutupi dengan asumsi atau konstruksi dugaan.
Lebih jauh, fakta empiris justru menunjukkan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024 menghasilkan Efisiensi Anggaran lebih dari Rp. 600 miliar serta berdampak pada penurunan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun berikutnya.
Badan Pusat Statistik juga mencatat Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2024 mencapai angka 88,20 yang masuk kategori sangat memuaskan. Fakta ini memperlemah argumentasi bahwa kebijakan tersebut secara kausal telah merugikan Keuangan Negara.
Dalam logika Hukum Pidana, tidak cukup hanya menunjukkan adanya dugaan penyimpangan, melainkan harus dibuktikan hubungan sebab akibat yang jelas antara kebijakan dan kerugian Negara yang nyata.
Apakah Gus Yaqut memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1 2023 jo. Pasal VII angka 55 UU NO. 1 tahun 2026?
Isu ketiga adalah apakah kebijakan tersebut dapat menjerat Yaqut Cholil Qoumas dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1 2023 jo. Pasal VII angka 55 UU NO. 1 tahun 2026. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 603 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menimbulkan kerugian keuangan negara.
Unsur-unsur ini bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam perkara ini, unsur melawan hukum masih diperdebatkan karena kebijakan tersebut memiliki dasar kewenangan undang-undang. Selain itu, hingga saat ini tidak terdapat bukti aliran dana atau keuntungan pribadi yang dinikmati oleh Yaqut Cholil Qoumas.
Dugaan adanya keuntungan yang dinikmati oleh pihak travel atau oknum bawahan tidak dapat secara otomatis dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana kepada Menteri tanpa pembuktian keterlibatan langsung dan kesengajaan.
Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 604 KUHP mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Unsur “dengan tujuan” menunjukkan adanya mens rea berupa kesengajaan sebagai maksud, yang harus dibuktikan secara positif.
Diskresi yang diambil berdasarkan kewenangan undang-undang, MOU bilateral, dan pertimbangan Keselamatan Jamaah tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Tanpa bukti adanya niat jahat dan tanpa pembuktian Kerugian Negara yang nyata, penerapan Pasal 3 / Pasal 604 KUHP menjadi problematis secara hukum.
Sejarah penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1 2023 jo. Pasal VII angka 55 UU NO. 1 tahun 2026 menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut kerap dikritik sebagai pasal yang sangat lentur dan rawan digunakan untuk mengkriminalisasi kebijakan publik.
Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah menegaskan bahwa Hukum Pidana tidak boleh digunakan untuk menghukum kesalahan kebijakan atau perbedaan Tafsir administratif.
Dalam Hukum Administrasi Negara, dikenal pembedaan yang tegas antara “maladministrasi” dan “penyalahgunaan wewenang”. Maladministrasi pada dasarnya berkaitan dengan cacat dalam tata kelola Pemerintahan, baik berupa kesalahan prosedur, kelalaian administratif, keterlambatan, ketidaktertiban, maupun ketidaktepatan dalam penggunaan instrumen hukum.
Maladministrasi tidak serta-merta mengandung unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan, melainkan lebih mencerminkan kegagalan administratif dalam menjalankan kewenangan secara optimal sesuai asas-asas umum Pemerintahan yang baik.
Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) merupakan tindakan pejabat yang secara sadar menggunakan kewenangan yang sah untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan tersebut.
Unsur utama dalam penyalahgunaan wewenang adalah adanya kehendak untuk mengalihkan fungsi kewenangan demi kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang memiliki dimensi kesalahan yang lebih berat dan dapat menjadi pintu masuk pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam konteks Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / Pasal 604 KUHP.
Dalam praktik penegakan hukum, garis pembatas antara maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang kerap menjadi kabur, terutama ketika suatu kebijakan administratif kemudian dikaitkan dengan dampak kerugian negara.
Padahal, tidak setiap cacat administrasi dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Hanya apabila terbukti adanya tujuan menyimpang, kesengajaan, serta hubungan kausal antara penggunaan kewenangan dan keuntungan pihak tertentu, maka suatu tindakan administratif dapat ditarik ke ranah pidana.
Rumusan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban hukum pejabat publik, agar hukum pidana tidak digunakan untuk mengkriminalisasi kebijakan atau kesalahan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Hukum Administrasi Negara.
Dalam konteks ini, menarik kebijakan pembagian kuota Haji tambahan 2024 ke ranah pidana korupsi tanpa pembuktian unsur-unsur delik secara ketat berpotensi mencederai asas kepastian hukum dan prinsip Negara Hukum.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam perkara pembagian kuota Haji tambahan tahun 2024 masih menyisakan persoalan serius secara Yuridis.
Kebijakan yang diambil berada dalam ranah kewenangan Administrasi Negara dan Diskresi Kebijakan, sementara unsur-unsur tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi secara utuh.
Jika memang terdapat perbuatan pidana, maka pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pelaku yang secara nyata melakukan dan menikmati hasil perbuatan tersebut, bukan dibangun atas dasar Jabatan atau tekanan Opini Publik semata.
Editor: S PNs