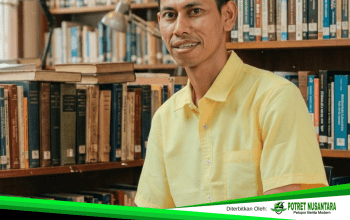Oleh: Ardillah Abu, S.Pd.,M.Pd
(Pemerhati Demokrasi-Akademis UIN Datokarama Palu)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id –
Demokrasi yang Menghitung
Demokrasi hari ini kerap dipersempit maknanya menjadi sekadar perlombaan angka. Siapa yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang di anggap paling sah memimpin. Logika ini perlahan menjadi dogma, seolah demokrasi hanya soal prosedur elektoral dan hitung-hitungan suara. Padahal, demokrasi bukan semata-mata teknik memilih, melainkan cara bangsa ini mengambil keputusan bersama secara bermartabat.
Dalam praktiknya, demokrasi prosedural sering kali melahirkan paradoks. Suara rakyat memang dikumpulkan, tetapi kehendak rakyat tidak selalu terwujud dalam kebijakan yang adil dan bijaksana. Ketika demokrasi direduksi menjadi mekanisme, substansinya justru terabaikan. Di sinilah pentingnya kita menimbang ulang arah demokrasi yang sedang kita jalani.
Sila Keempat dan Jiwa Demokrasi Indonesia
Para pendiri bangsa tidak meletakkan demokrasi Indonesia di atas fondasi liberalisme Barat. Sila ke-4 Pancasila secara sadar menegaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Frasa di atas bukan hiasan konstitusional, melainkan penegasan bahwa suara rakyat harus dipandu oleh kebijaksanaan, bukan oleh emosi sesaat atau kepentingan jangka pendek.
Musyawarah dalam konteks Pancasila bukanlah kelemahan demokrasi, tetapi justru kekuatannya. Ia mengedepankan proses dialog, pertimbangan moral, dan pencarian titik temu. Demokrasi tidak dimaknai sebagai siapa yang paling kuat atau paling banyak, melainkan siapa yang paling mampu menghadirkan kemaslahatan bersama.
Tradisi Nusantara: Demokrasi Sebelum Negara
Jauh sebelum republik ini berdiri, masyarakat Nusantara telah mempraktikkan demokrasi dalam bentuknya yang paling substansial. Dalam berbagai komunitas adat, keputusan penting selalu di ambil melalui musyawarah. Suara masyarakat disalurkan melalui figur-figur yang dipercaya: orang tua adat, kepala suku, tokoh agama, atau pemimpin informal yang memiliki otoritas moral.
Kebiasaan merujuk kepada “orang tua” dalam memutuskan perkara bersama bukanlah bentuk feodalisme, melainkan mekanisme sosial untuk memastikan keputusan diambil secara bijak. Pak haji, pendeta, imam, atau tetua adat tidak dipilih melalui kampanye, tetapi melalui rekam jejak integritas dan kearifan. Disana, legitimasi lahir dari kepercayaan, bukan dari popularitas.
Menariknya, negara yang sering dijadikan rujukan demokrasi modern justru tidak sepenuhnya mempraktikkan pemilihan langsung.
Presiden Amerika Serikat dipilih melalui sistem “Electoral College”, bukan semata-mata berdasarkan jumlah suara rakyat. Artinya, pemenang pemilu ditentukan oleh perolehan suara elektoral yang merepresentasikan negara bagian, bukan oleh prinsip one man one vote secara murni. Kasus Hillary Clinton pada Pemilu 2016 menjadi contoh nyata.
Ia memperoleh suara rakyat lebih banyak daripada Donald Trump, tetapi tetap kalah karena Trump unggul dalam suara elektoral. Fakta ini menunjukkan bahwa bahkan demokrasi liberal pun mengakui pentingnya mekanisme perwakilan dan struktur institusional, bukan sekadar akumulasi suara individu.
Pada Pemilu 2020, Joe Biden memang memenangkan suara rakyat sekaligus suara elektoral, sehingga sah dilantik sebagai presiden. Namun dinamika ini tetap menegaskan satu hal penting: demokrasi Amerika bukan demokrasi langsung dalam pengertian yang sering kita bayangkan. Demokrasi selalu merupakan hasil kompromi antara suara rakyat, elit politik, dan desain kelembagaan.
Di titik inilah kita perlu bercermin. Ketika negara lain mempertahankan sistem perwakilan demi stabilitas dan kebijaksanaan institusional, kita justru kerap meragukan model musyawarah yang menjadi jati diri bangsa sendiri. Kita sibuk meniru, tetapi lupa pada akar.
Menimbang ulang demokrasi kita bukan berarti mundur dari kemajuan, melainkan mengembalikan demokrasi pada makna aslinya “sebagai sarana menghadirkan keadilan dan kemaslahatan”. Demokrasi Pancasila menuntut lebih dari sekadar suara terbanyak; ia menuntut hikmah, etika, dan tanggung jawab moral.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang paling riuh oleh suara, melainkan demokrasi yang paling tenang dalam kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu, sesungguhnya telah lama hidup dalam tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu kita.
Editor: S PNs