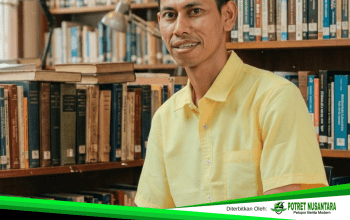Oleh: Abhy Muhammad
Direktur Lontara Institute
Karema, 22 Agustus 2025 – Di abad pertengahan, feodalisme ialah sistem di mana orang yang menguasai tanah memiliki kedudukan tertinggi. Raja menyerahkan tanah kepada bangsawan, lalu bangsawan memberikannya kepada kesatria, dan kesatria membagikannya kepada masyarakat. Pada lapisan piramida paling bawah terdapat para petani yang bekerja tanpa memiliki kuasa sedikit pun.
Kalau dilihat, hubungan ini sederhana namun kejam: tanah ditukar dengan loyalitas, perlindungan ditukar dengan ketaatan, hierarki sosial terkunci rapat, dan mobilitas hampir mustahil bagi masyarakat kecil kala itu.
Namun, di era disrupsi sekarang, cerita feodalisme bukan sekadar masalah sejarah lalu. Bayangannya masih terasa hingga hari ini, di negeri kita, ketika birokrasi tunduk bukan pada aturan, tetapi pada figur atasan. Ketika jabatan masih diberikan dan diwariskan lewat jejaring patronase serta loyalitas, bukan pada kompetensi, dengan sendirinya kita mafhum bahwa praktik-praktik feodalisme masih sangat kental melingkupi kita.
Sebagian petikan narasi ini sebenarnya saya kutip dari konten Rahmani Blog, yang benar-benar membuat saya tertegun.
Jika ditelusuri, feodalisme berakar sejak sistem pemerintahan Hindu-Buddha dan Islam, lalu berlanjut pada sistem kolonial Hindia-Belanda yang bekerja sama dengan para raja untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan kekuasaan.
Bayangkan, sistem sosial-politik pada era praaksara hingga Nusantara terbentuk menjadi Negara Republik Indonesia masih berlanjut dan dilestarikan sampai hari ini. Sekurang-kurangnya gejala ini berangkat dari struktural, kemudian menjadi kultural, seakan-akan menjadi bagian dari diri kita, menjelma menjadi budaya, dan kita bersikap take it for granted.
Ketika situasi itu terus berlanjut, rakyat kecil menunduk kepada elite demi sepotong akses dan perlindungan. Maka, di situlah mental feodal bersemayam.
Feodalisme modern tidak lagi berbicara tentang tanah dan kesatria, melainkan tentang bagaimana orang dibuat bergantung pada tuan-tuan besar, pada figur atasan yang memiliki otoritas lebih dari bawahannya. Padahal bangsa merdeka seharusnya berdiri di atas kakinya sendiri. Semangat perjuangan maupun cita-cita Reformasi 1998 berbicara tentang kesetaraan dan ketundukan terhadap hukum, bukan pada bayang-bayang feodalisme yang hanya melahirkan ketidakadilan serta ketimpangan sosial.
Sayangnya, Reformasi 1998 seperti angin segar yang berlalu begitu cepat; kilatnya menggelegar namun hilang di siang bolong, membawa obor di kegelapan, namun padam diterpa gelombang demokrasi berwajah oportunis.
Wajar jika hari ini pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara mendapatkan banyak kritikan. Sebab, ditinjau dari aspek sosial-politik dan sosial-ekonomi, Indonesia seakan berjalan sempoyongan. Seperti petikan terakhir Prof. Nadirsyah Hosen dalam tulisannya “Rebut Kembali Demokrasi dari Tangan Oligarki”, beliau mengatakan: “Demokrasi Indonesia tidak boleh terus jadi ladang investasi para oligarki.”
Meski feodalisme dan oligarki memiliki pemaknaan berbeda dalam konteks sosial-politik, keduanya memiliki hubungan erat. Keduanya sama-sama berpusat pada kelompok kecil yang menguasai sumber daya dan kekuasaan.
Jika kita benar-benar ingin mengikis feodalisme, jangan memulainya dari istana raja-raja, atau dari gedung parlemen para tuan kecil.
Mari mulai dari ruang kelas, kampus, dan universitas. Sebab, dari situlah ketundukan, kepatuhan, dan nalar kritis diajarkan. Sekolah bukan sekadar tempat belajar mengajar, melainkan ruang pembentukan nilai dan karakter. Di kampus dan universitas, transformasi ilmu seharusnya ditularkan secara jujur dan sejajar. Pendidikan adalah mesin paling ampuh untuk melawan penyelewengan moral.
Namun, pertanyaan yang paling elementer adalah: beranikah para guru dan dosen memulai? Sebab, sering kali pengajar memposisikan diri sebagai tuan kecil, maha tahu segalanya, tak boleh disanggah, memperlakukan siswa atau mahasiswa sebagai objek, bukan subjek dalam proses belajar. Model seperti ini disebut pedagogi pembelajaran anak-anak.
Padahal, dalam upaya melenyapkan mental feodal, perubahan harus dimulai dari pikiran. Artinya, guru dan dosen harus rela turun dari dominasi, dari otoritas yang membelenggu cara berpikir peserta didiknya. Membiarkan siswa bertanya, membuka dialog dengan mahasiswa, hanya dengan cara seperti ini kita bisa membentuk karakter, menumbuhkan keberanian, dan melahirkan manusia merdeka dalam berpikir.
Selain pandangan di atas, ada tawaran lain dari cendekiawan muslim Nurcholish Madjid dalam bukunya Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Ia mengatakan: “Untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih ialah memperkuat orientasi-orientasi etika berdasarkan agama.” Terutama bagi umat Islam, sebab menurut Cak Nur, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan sumber ajarannya untuk memperkuat orientasi etika.
Meskipun gagasan itu memiliki konteks tersendiri, dalam pembacaan Cak Nur terkait demokrasi dan politik, tampaknya ia ingin agar nilai-nilai Islam menjadi panduan bernegara. Sebagaimana ia katakan, nilai Islam sudah terdapat dalam ideologi nasional, yakni Pancasila.
Dengan menempuh jalan onak berduri ini, Indonesia hanya bisa diselamatkan dari rembesan mental feodal yang telah merentang sepanjang sejarah dan merasuk ke sendi kehidupan.
Perjuangan bangsa kita hari ini tidaklah sesederhana yang dibayangkan, sama beratnya ketika para perintis kemerdekaan membebaskan masyarakat dari belenggu feodalisme kolonial. Kini tanggung jawab berada di pundak kita. Mungkin terdengar mudah, tetapi sesungguhnya sangat berat.
Sekolah dan universitas adalah tumpuan harapan bangsa. Sayangnya, kadang hanya terpacu menambah nominal sarjana, namun minim melahirkan intelektual. Oleh sebab itu, mari kita jadikan sekolah dan kampus sebagai rumah kebebasan berpikir, bukan kepatuhan.
Jika para dosen dan guru sudah berani memulai, kita akan melahirkan generasi yang mampu berdiri sendiri, bukan generasi yang terus menunduk.
Dan boleh jadi, cita-cita bangsa Indonesia dalam menyambut 2045, bonus demografi menuju Indonesia Emas, harus dipersiapkan sedari sekarang. Jika hari ini kita gagal, konsekuensi logisnya adalah menerima kenyataan pahit: bangsa ini hanya akan melahirkan generasi dengan mental neo-feodalisme.