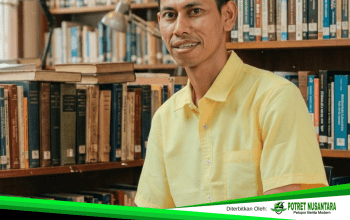Oleh: Dr. Muhammad Alwi, S.Sy.,M.E.I
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Di tengah kemajuan teknologi keuangan, masyarakat dihadapkan pada sebuah paradoks baru yaitu kemudahan yang menjanjikan kenyamanan, tetapi secara perlahan menanamkan ketergantungan.
Salah satu manifestasinya adalah maraknya skema “Buy Now Pay Later” (BNPL) bisa beli sekarang, bayar nanti yang kini menjelma bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan gaya hidup. Utang tak lagi dipandang sebagai jalan darurat, tetapi bagian dari rutinitas konsumsi harian.
BNPL hadir dengan berbagai kemudahan tanpa kartu kredit, persetujuan instan, cicilan ringan, bahkan sering kali dibungkus promosi tanpa bunga.
Dalam praktiknya, skema ini mendorong konsumen untuk mengambil keputusan cepat, nyaris tanpa jeda refleksi. Barang dibeli hari ini, kewajiban dipikirkan kemudian. Di sinilah persoalan bermula yaitu kemudahan teknologi mendahului kesadaran etis.
Fenomena BNPL menunjukkan bagaimana logika konsumsi modern secara halus menggeser orientasi hidup manusia dari kecukupan menuju keinginan yang tak pernah selesai.
Barang-barang yang sejatinya tidak terlalu esensial dengan gawai terbaru, fashion musiman, hingga simbol status digital kemudian dikemas seolah menjadi kebutuhan primer. Utang pun dinormalisasi, bahkan dirayakan, selama cicilan terasa ringan.
Di titik inilah terjadi krisis kesadaran, dimana rasionalitas ekonomi digantikan oleh rasionalisasi nafsu, sementara kemampuan menahan diri perlahan terkikis oleh kemudahan teknologi.
Salah satu perkara serius dalam pandangan Islam adalah utang. Rasulullah saw, dikenal sangat berhati-hati terhadap persoalan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmād dan At-Tirmīdzi, Rasulullah saw bersabda:
“Jiwa seorang mukmin tergantung oleh utangnya hingga utang itu dilunasi”.
Hadis ini menegaskan bahwa utang bukan urusan administratif semata, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual seorang hamba.
Al-Qur’ān bahkan sejak awal menegaskan prinsip pengelolaan harta yang beradab:
“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Qs. Al-A’rāf: 31).
Ayat ini bukan sekadar seruan moral individual, melainkan fondasi etika ekonomi Islam. Ketika konsumsi melampaui batas kemampuan, dan utang dijadikan jalan pintas untuk memenuhi keinginan, maka yang runtuh bukan hanya keseimbangan finansial, tetapi juga disiplin spiritual seorang Muslim.
Dalam praktik BNPL, batas antara kebutuhan dan keinginan sering kali menjadi kabur. Skema cicilan menciptakan ilusi kemampuan bayar, sementara akumulasi kewajiban tersembunyi di balik nominal kecil.
Tanpa literasi keuangan yang memadai, konsumen mudah terjebak dalam lingkaran utang berlapis. Pada titik ini, utang tidak lagi memberdayakan, tetapi justru membelenggu.
Ajaran Islam tidak mengharamkan utang, tetapi menempatkannya dalam kerangka darurat dan tanggung jawab. Utang dibolehkan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, disertai niat kuat untuk melunasi.
Rasulullah saw, bahkan berdoa agar dilindungi dari lilitan utang;
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan lilitan utang”.
Ketika ditanya mengapa utang disandingkan dengan dosa? Beliau menjelaskan bahwa “Orang berutang kerap tergelincir pada kebohongan dan pengingkaran janji”. (HR. Bukhāri dan Muslim).
Budaya BNPL berisiko menumbuhkan sikap sebaliknya yaitu meremehkan utang, menormalisasi penundaan kewajiban, dan mengikis rasa tanggung jawab finansial. Jika dibiarkan, masyarakat dapat tumbuh dalam struktur ekonomi yang rapuh_ tampak sejahtera di permukaan, namun rapuh di kedalaman.
Utang konsumtif yang meluas bukan hanya masalah individu, melainkan persoalan sosial. Dari perspektif ekonomi syariah, persoalan ini bersentuhan langsung dengan tujuan besar (maqāshid al-syarī’ah), khususnya pada perlindungan harta (hifzh al-māl) dan jiwa (hifzh al-nafs).
Tekanan psikologis akibat utang, kecemasan menghadapi jatuh tempo, hingga konflik rumah tangga adalah dampak nyata yang sering luput dari perhitungan ekonomi. Utang yang tidak terkelola dengan baik bukan sekadar masalah angka, tetapi masalah kemanusiaan.
Karena itu, kritik terhadap budaya BNPL tidak cukup berhenti pada aspek teknis atau regulasi semata. Yang lebih mendesak adalah membangun kesadaran etik dan spiritual dalam konsumsi.
Literasi keuangan harus berjalan seiring dengan literasi akhlak. Masyarakat perlu kembali membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara cukup dan berlebih.
Negara dan otoritas keuangan tentu memiliki peran penting dalam pengawasan dan edukasi. Namun, tanggung jawab utama tetap berada pada individu dan keluarga.
Islam mengajarkan qanā’ah (merasa cukup) sebagai benteng dari kerakusan. Dalam kesederhanaan itulah sesungguhnya terletak kemerdekaan ekonomi.
Pada akhirnya, persoalan BNPL bukan semata tentang teknologi pembayaran, melainkan tentang arah peradaban ekonomi yang sedang kita bangun. Ketika utang menjadi gaya hidup, dan keinginan disamarkan sebagai kebutuhan, maka yang terancam bukan hanya stabilitas keuangan, tetapi juga kejernihan nurani.
Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bukan terletak pada kemampuan membeli apa saja, melainkan pada kemampuan menahan diri. Di sanalah kekuatan umat terletak pada kesadaran, bukan pada cicilan.
“Penulis adalah Akademisi UIN Palopo dan saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”.
Editor: S PNs