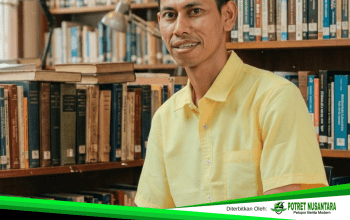Oleh: Aa Muhamad Zaenudin, S.A.P.,S.H., M.H.
(Ketua LBH GP Ansor Bekasi)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Perdebatan hukum yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sejatinya membuka kembali persoalan klasik dalam hukum pidana Indonesia, sejauh mana kebijakan publik dapat ditarik ke ranah pidana korupsi.
Isu ini tidak berdiri dalam ruang hampa. Ia bersentuhan langsung dengan problem laten Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sejak awal kelahirannya memang menyimpan problem konseptual serius.
Kedua pasal tersebut, bahkan sebelum kemudian “digantikan” dalam kodifikasi baru melalui Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, kerap dipandang sebagai pasal multitafsir, bahkan cenderung berwatak “pasal karet”.
Problemnya bukan semata pada ancaman pidananya, melainkan pada rumusan delik yang membuka ruang tafsir berlebihan terhadap unsur “actus reus” dan “mens rea”.
Sampai hari ini pun, aparat penegak hukum dan para ahli hukum pidana belum mencapai kesepakatan yang solid mengenai batasan objektif dan subjektif kedua unsur tersebut. Padahal, dalam hukum pidana modern, perumusan delik tidak boleh ambigu, apalagi ditafsirkan secara analogi.
Di sinilah asas “lex certa” dan “lex stricta” seharusnya berdiri sebagai pagar. Lex certa menuntut agar rumusan delik pidana jelas dan tegas, sedangkan lex stricta mengharuskan norma pidana dimaknai secara ketat tanpa perluasan makna melalui analogi.
Ketika pasal korupsi justru lentur dan elastis dalam penafsiran, maka yang terancam bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga keberanian pejabat publik dalam mengambil kebijakan.
Secara universal, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage), baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.
Inti delik korupsi bukan terletak pada kontroversi kebijakan, melainkan pada adanya niat jahat untuk memperkaya diri atau pihak tertentu. Tanpa unsur itu, hukum pidana kehilangan legitimasi moralnya dan berubah menjadi alat penghukuman kebijakan.
Kesadaran akan bahaya tersebut, sebenarnya telah tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Menariknya, dalam putusan ini terdapat pandangan berbeda (dissenting opinion) dari empat Hakim Konstitusi, yakni: I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, dan Maria Farida Indrati.
Para hakim ini menegaskan bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, justru dirancang sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya.
Undang-undang ini menempatkan dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dalam rezim Hukum Administrasi, bukan langsung Pidana. Melalui mekanisme pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara serta pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Negara menyediakan filter awal sebelum suatu tindakan administratif ditarik ke ranah pidana.
Dengan mekanisme tersebut, Aparat Penegak Hukum tidak dapat serta-merta mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang maupun kerugian negara tanpa terlebih dahulu adanya penilaian administratif yang sah.
Dalam konteks inilah, perlindungan hukum bagi Gus Yaqut harus dipahami. Kebijakan pembagian kuota haji tambahan, betapapun diperdebatkan secara politik dan administratif, tetaplah sebuah kebijakan publik yang lahir dari kewenangan atribusi undang-undang.
Selama tidak terbukti adanya tujuan menyimpang untuk memperkaya diri atau pihak tertentu, serta belum dinyatakan sebagai penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme hukum administrasi, maka menariknya langsung ke dalam konstruksi delik korupsi adalah langkah yang tergesa dan berbahaya.
Pada akhirnya, hukum pidana harus tetap ditempatkan sebagai “ultimum remedium”, bukan sebagai alat untuk mengoreksi setiap kebijakan publik yang kontroversial.
Perlindungan hukum terhadap pejabat yang bertindak dalam koridor kewenangan dan itikad baik bukanlah bentuk impunitas, melainkan syarat mutlak bagi lahirnya pemerintahan yang berani, rasional, dan bertanggung jawab.
Dalam konteks Gus Yaqut, perlindungan hukum tidak dimaksudkan untuk menutup ruang kritik atau pengawasan, tetapi untuk memastikan agar hukum tetap bekerja secara proporsional dan berakal sehat.
Memang, Hukum Pidana menilai perbuatan konkret dan mengujinya berdasarkan norma yang berlaku. Namun, ketika norma tersebut bermasalah, multitafsir, dan membuka ruang penafsiran yang berlebihan, maka ancaman daluwarsa delik korupsi yang sangat panjang justru menciptakan ketidakpastian hukum.
Pejabat yang telah lama tidak menjabat pun berpotensi terus dicari-cari kesalahannya dan diseret ke pengadilan atas kebijakan yang diambil di masa lalu, meskipun kebijakan tersebut lahir dari diskresi dan pertimbangan kepentingan umum.
Karena itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak boleh bergeser menjadi instrumen kekuasaan, baik sebagai titipan kepentingan politik maupun sebagai sarana menakut-nakuti pejabat publik.
Hukum harus menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan keberanian mengambil keputusan, agar negara tidak terjebak dalam pemerintahan yang lumpuh oleh ketakutan, tetapi tetap bergerak dalam koridor hukum yang adil dan bermartabat.
Editor: S PNs