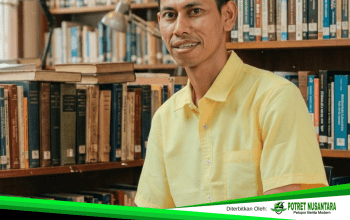Oleh: Mohammad Nayaka Rama Yoga
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Saya selalu percaya bahwa salah satu misteri paling membingungkan dalam kehidupan sosial bukanlah kenapa dinosaurus punah, bukan pula kenapa harga telur dan daging bisa naik turun dengan drastis yang bikin jantung dan dompet member gym majapahit deg-degan setiap harinya, bukan bukan. Tetapi, persoalan kenapa orang yang berhutang seringkali lebih galak daripada yang memberi hutang. Fenomena ini begitu ajaib sampai rasanya saya sebagai sosiolog perlu membuat seminar dan konferensi khusus untuk membahasnya di depan para debt collector dan mata elang. Namun sebelum itu terjadi, izinkan saya sebagai seorang sosiolog muda lagi amatir ini memberikan sedikit opini yang kelihatannya akan masuk akal dan bisa menjawab pertanyaan di atas.
Pertama-tama, memahami masalah hutang tidak bisa disederhanakan hanya sekadar permasalahan angka dan nominal di atas bon saja. Menurut Karl Polanyi (1944), permasalahan ekonomi manusia tidak akan terpisahkan dengan permasalahan sosial. Ini artinya ketika seseorang berhutang, dirinya sedang membuka pintu kehidupan sosial yang baru, mulai dari hubungan baik dengan pemberi hutang, sampai hubungan buruk dengan perasaan malu. Sayangnya, pintu yang dibuka itu sering berakhir menjadi pintu darurat, apalagi ketika tanggal jatuh tempo sudah lewat beberapa kali dan pemberi hutang tiba-tiba muncul sambil membawa senyum tipis yang penuh makna.
Dalam kondisi seperti ini, muncul lah reaksi klasik dari para peminjam, yaitu memberikan reaksi yang bersifat defensif berupa gestur galak dan marah-marah kepada yang menagih. Jangan salah, menurut Erving Goffman (1955), manusia punya kebutuhan emosional untuk menjaga “muka” atau citra diri. Bayangkan, Anda punya hutang, terus ditagih di depan warung, dan semua mata tetangga Anda tiba-tiba menoleh. Pada saat itu, harga diri Anda pasti akan jatuh lebih cepat. Maka untuk menyelamatkan harga dirinya, muncullah reaksi-reaksi negatif seperti meninggikan suara, mengerutkan alis, dan memunculkan berbagai argumen yang terkadang lebih panjang dari kultum menjelang buka puasa. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, yakni menunjukkan bahwa dirnya “tidak salah-salah amat” ketika tidak membayar hutang.
Namun fenomena ini tidak berhenti di situ. Dalam relasi sosial kita sehari-hari, apalagi pada hutang antar kerabat, tetangga, atau teman, justru pemberi hutang sering berada pada posisi serba salah. Kita dapat menemukan jawaban dari fenomena di atas dari James C. Scott (1976). Dalam teorinya yang diberi nama moral economy, ia menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang menjunjung nilai gotong royong, pemberi hutang dianggap harus memiliki sikap empati, sabar, tahan banting, dan tidak boleh terlihat rakus dalam menyikapi permasalahan yag berkaitan dengan uang. Mau menagih terlalu tegas nanti dikira tidak punya hati. Mau menagih pelan-pelan malah diremehkan. Akibatnya, pemberi hutang sering tak berkutik, sementara peminjam merasa punya ruang untuk sedikit menaikkan volume suara yang tentu saja itu dilakukan untuk mendominasi suasana.
Di sisi lain, faktor ekonomi juga tak bisa diabaikan. Orang yang sedang kesulitan ekonominya biasanya sedang berada dalam mode “survival”. Dalam dunia psikologi, ada istilah yang biasa disebut sebagai displaced aggression, yaitu suatu kondisi dimana seseorang akan melampiaskan stres pada orang-orang yang mudah dijangkau. Bourdieu (1984) pun menunjukkan bahwa kelompok ekonomi menengah-bawah sering mempertahankan harga diri dengan sikap keras sebagai kompensasi atas kondisi sosial yang tidak menguntungkan. Jadi sebenarnya, ketika peminjam galak, itu bukan karena mereka itu punya power, tetapi justru karena ia sedang paling rapuh. Hanya saja, sayangnya, ia memilih gaya rapuh yang berisik.
Budaya kita juga memberikan kontribusi besar pada kebiasaan masyarakat kita menyikapi dunia perhutangan. Jika hutang dianggap hal biasa, seperti meminjam garam atau kecap ke tetangga, maka sebagian orang merasa tak perlu terlalu khawatir soal tenggat waktunya. Diane Vaughan (1996) menyebut ini sebagai normalization of deviance, yaitu sebuah perilaku salah yang dianggap benar karena banyak orang melakukannya. Maka ketika ditagih, peminjam merasa dirinya tidak melakukan tindakan luar biasa. Kalau ditagih terlalu sering, malah pemberi hutang yang dianggap berlebihan, dan muncullah adegan galak sebagai bentuk pembalikan logika moral.
Pada akhirnya, yang bertarung dalam masalah hutang bukan hanya uang, tetapi juga moral, rasa malu, dan kebutuhan manusia untuk terlihat sebagai makhluk yang “baik-baik saja”. Viviana Zelizer (2012) menegaskan bahwa uang juga punya makna sosial. Ketika hutang masuk ke hubungan antar manusia, hutang bisa berubah menjadi adonan rumit antara ekonomi dan perasaan. Maka jangan kaget jika peminjam lebih galak dari pemberi hutang. Hal itu hanyalah cara mereka untuk menata ulang dunianya yang sudah kacau sejak tanggal jatuh tempo sudah lewat seminggu yang lalu.
Jadi, jika suatu hari Anda menagih hutang dan justru malah dimarahi, bersikaplah tenang. Jangan langsung sakit hati oleh mereka para debitur. Ingatlah bahwa Anda sedang berhadapan dengan sebuah fenomena yang telah dijelaskan oleh para pemikir-pemikir besar di atas. Dan ingatlah pula bahwa kadang-kadang, marah adalah bahasa lain dari “saya malu dan bingung harus bagaimana lagi”. Jika kita dapat memahami fenomena ini dengan bijak, ini akan membuat kita sedikit lebih sabar. Tapi, ya tetap saja dong… hutang tetaplah hutang, kan? Bayar dong……
Referensi:
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste (R. Nice, Trans.). Harvard University Press.
Goffman, E. (1955). On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction. Psychiatry: Journal for the Study of Interpersonal Processes, 18(3), 213–231.
Polanyi, K. (1944). The great transformation: The political and economic origins of our time. Beacon Press.
Scott, J. C. (1976). The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia. Yale University Press.
Vaughan, D. (1996). The challenger launch decision: Risky technology, culture, and deviance at NASA. University of Chicago Press.
Zelizer, V. A. (2012). Economic lives: How culture shapes the economy. Princeton University Press.