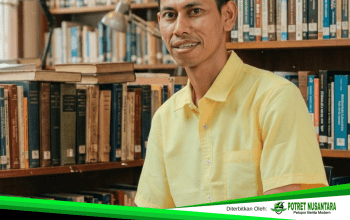Oleh: Muhadir Azis, S.Pd.I.,M.Pd
(Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan GP Ansor Palopo – Akademisi UIN Palopo)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Di tengah derasnya arus digital, ilmu pengetahuan kini hadir begitu dekat dan mudah diakses. Dengan satu gawai, berbagai informasi dan pengetahuan dapat diperoleh dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul kegelisahan yang patut direnungkan: semakin banyak orang merasa berilmu, tetapi semakin sedikit yang peduli terhadap asal-usul ilmu yang dipelajarinya.
Dalam tradisi keilmuan Islam, persoalan asal-usul ilmu bukanlah hal sepele. Para ulama sejak masa awal menaruh perhatian besar terhadap sanad, yaitu rantai transmisi ilmu dari guru kepada murid. Abdullah bin al-Mubarak, seorang ulama besar generasi awal Islam, menegaskan bahwa sanad merupakan bagian penting dari agama. Pernyataan ini mengandung makna bahwa ilmu harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar hasil dari opini atau pengetahuan tanpa dasar yang jelas.
Pengenalan terhadap tokoh dalam sanad keilmuan bukan sekadar upaya mengenang nama-nama besar masa lalu. Lebih dari itu, pengenalan tokoh merupakan ikhtiar menjaga kualitas dan arah ilmu. Al-Ghazali, misalnya, menempatkan guru sebagai unsur utama dalam pembentukan kepribadian ilmuwan. Menurutnya, ilmu yang tidak membentuk akhlak hanya akan melahirkan kecerdasan yang kering nilai.
Oleh karena itu, mengenal tokoh dalam sanad keilmuan berarti memahami nilai, etika, dan keteladanan yang menyertai proses pewarisan ilmu. Pemikiran serupa juga disampaikan oleh Ibn Khaldun. Ia menjelaskan bahwa ilmu berkembang melalui proses pewarisan antargenerasi.
Pengetahuan tidak lahir secara instan, melainkan tumbuh melalui pengalaman, dialog, dan tradisi intelektual para pemikir sebelumnya. Ketika tokoh-tokoh dalam rantai keilmuan diabaikan, ilmu kehilangan konteks historis dan sosialnya, sehingga mudah disalahpahami atau disalahgunakan.
Kondisi ini semakin terasa dalam dunia pendidikan modern. Tidak sedikit pelajar dan mahasiswa yang menguasai istilah serta konsep, tetapi tidak mengenal para perintis pemikiran tersebut. Nama tokoh sering kali hadir sebatas formalitas akademik dalam daftar pustaka, tanpa upaya memahami gagasan dan kontribusinya secara utuh.
Akibatnya, ilmu diperlakukan sebagai kumpulan informasi, bukan sebagai amanah intelektual yang menuntut tanggung jawab moral. Fenomena serupa juga tampak dalam ruang dakwah digital. Media sosial dipenuhi berbagai konten keagamaan yang cepat menyebar dan menarik perhatian publik. Namun, tidak sedikit di antaranya yang minim rujukan dan kedalaman keilmuan.
Popularitas kerap dijadikan ukuran kebenaran, sementara otoritas ilmu dan tradisi keilmuan justru terpinggirkan. Tanpa pengenalan tokoh dan sanad keilmuan, dakwah berisiko kehilangan pijakan dan arah. Kehadiran kecerdasan buatan (AI) semakin mempertegas tantangan tersebut. Teknologi ini mampu menyajikan jawaban yang cepat dan sistematis, tetapi tidak memiliki sanad, pengalaman, maupun tanggung jawab moral.
Apabila manusia sepenuhnya bergantung pada mesin tanpa kesadaran keilmuan yang memadai, maka hubungan dengan tradisi intelektual yang matang akan terputus. Ilmu menjadi tampak canggih, tetapi sesungguhnya dangkal.
Mengenal tokoh dalam sanad keilmuan sejatinya merupakan latihan kerendahan hati intelektual. Kesadaran ini mengajarkan bahwa pengetahuan yang dimiliki hari ini merupakan hasil jerih payah panjang para ulama dan pemikir sebelumnya.
Dengan mengenal tokoh, sikap kritis dapat tumbuh tanpa kehilangan adab, dan kemajuan dapat diraih tanpa tercerabut dari akar tradisi. Oleh karena itu, menghidupkan kembali kesadaran akan sanad keilmuan merupakan kebutuhan mendesak.
Kampus, ruang dakwah, dan media digital perlu bersama-sama menempatkan ilmu pada martabatnya. Tanpa pengenalan tokoh, ilmu memang tetap beredar, tetapi fondasi intelektualnya rapuh. Ilmu yang rapuh akan sulit memberikan arah, pencerahan, dan kemaslahatan bagi umat.
Editor: S PNs