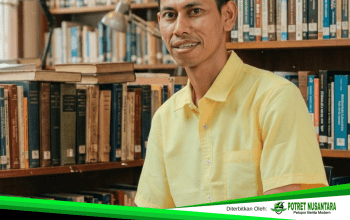Oleh: Suherman Syach
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Belakangan ini, linimasa kembali ramai oleh perbincangan tentang pesantren. Gara-gara satu tayangan televisi yang menyorot sisi “gelap” kehidupan santri, publik tiba-tiba berubah jadi pakar kepesantrenan. Ada yang bersimpati, tapi tak sedikit yang mencibir. Konon katanya, santri dipekerjakan, disuruh kerja, bahkan dieksploitasi.
Saya tersenyum saja. Sebagai alumni pesantren, saya maklum: mereka yang nyinyir itu mungkin belum pernah merasakan tidur beralas tikar, makan seadanya, atau rebutan air di sumur untuk mandi atau air wudhu sebelum subuh. Mereka hanya menilai pesantren dari tayangan tiga menit di TV, bukan dari ratusan malam panjang penuh doa, hafalan, dan kerja keras yang dijalani ribuan santri di seluruh negeri.
Pesantren adalah universitas kehidupan. Di sana, ilmu tak hanya berputar di kepala, tapi meresap ke hati dan menggerakkan tangan. Pendidikan di pesantren tak berhenti pada kognitif, tapi menembus afektif, psikomotorik, bahkan religiusitas dan spiritualitas. Di sana, anak muda ditempa menjadi manusia seutuhnya bukan hanya pandai bicara, tapi juga pandai berbuat.
Subuh hari belajar ilmu al- Quran dan al-Hadist, siang belajar di kelas hingga sore, malam mengaji. Di sela-sela kegiatan wajib tersebut, santri (baca: dulu) harus berjibaku di dapur dan sumur untuk memasak dan memasak sendiri. Santri itu tak perlu modul soft skill, mereka belajar kepemimpinan dari antrean kamar mandi, belajar manajemen waktu dari jadwal salat berjamaah, dan belajar tanggung jawab.
Tapi sayangnya, publik modern sering gagal memahami filosofi itu. Ketika melihat santri ikut membangun gedung asrama, mereka langsung menuduh “pesantren memperkerjakan anak”. Padahal, bagi kami, itu bukan kerja paksa, melainkan kerja ikhlas bagian dari kurikulum kehidupan.
Saya masih ingat, dulu di pondok saya sempat jadi peternak ayam. Bangun sebelum azan subuh, kasih makan ayam, bersihin kandang, lalu berangkat mengaji. Apakah itu melelahkan? Tentu. Tapi dari situ saya belajar tanggung jawab, disiplin, dan kesabaran.
Sekarang, lihatlah para alumni pesantren: ada yang jadi dosen, wartawan, pengusaha, bahkan pejabat publik. Banyak dari mereka lahir dari tangan-tangan yang dulu “mengangkat batu”, tapi kini mengangkat harkat bangsa. Jadi kalau hari ini ada yang menyindir santri sebagai “kuli”, barangkali mereka lupa: bangsa ini berdiri dari tangan para santri yang rela jadi kuli perjuangan.
Ada ironi yang menggelitik. Ketika sekolah modern meluncurkan program project-based learning, publik bertepuk tangan: “Wah, inovatif! Siswa belajar lewat pengalaman.”
Tapi ketika pesantren melakukan hal serupa sejak puluhan tahun lalu — belajar lewat praktik, gotong royong, dan kemandirian — mereka dicap kolot dan ketinggalan zaman, bahkan melanggar ham.
Mungkin karena di pesantren tak ada istilah teknologi yang keren. Kami tidak menyebutnya entrepreneurship training, hanya ngurus koperasi santri. Kami tak menyebutnya leadership camp, cukup rihlah ukhuwah. Tapi esensinya sama: melatih hidup yang nyata.
Santri adalah simbol manusia Indonesia: mandiri, tangguh, berjiwa sosial, dan religius. Mereka diajarkan untuk tidak bergantung, tidak mudah mengeluh, dan selalu bersyukur dalam kesederhanaan. Maka wajar bila dari pesantren lahir tokoh-tokoh besar, ulama, pemimpin, dan intelektual bangsa.
Kita boleh berbeda pandangan tentang metode pendidikan, tapi meremehkan pesantren sama saja dengan meremehkan salah satu fondasi moral bangsa. Pesantren telah berjasa membentuk karakter ribuan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi matang secara spiritual dan sosial.
Tentang Penulis:
Suherman adalah alumni pesantren dan Kepala Humas IAIN Parepare. Aktif menulis opini dan refleksi sosial tentang pendidikan, komunikasi publik, dan kehidupan santri