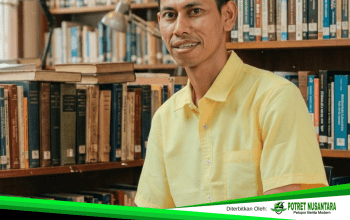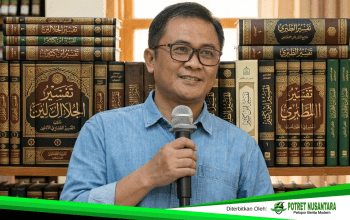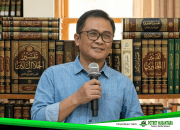Oleh: Dini Febriani
(Peserta LKK HMI Cabang Pangkep)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Demokrasi sejatinya bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan ruang perjuangan nilai. Dalam konteks ini, partisipasi politik perempuan tidak dapat lagi dimaknai sebatas pemenuhan angka kuota, tetapi harus diarahkan pada keterlibatan yang substantif, bermakna, dan berdaya ubah. Sebab politik, sebagaimana ditegaskan Harold D. Lasswell, adalah soal siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.
Maka ketika perempuan absen atau hanya hadir secara simbolik, kepentingan mereka kerap terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan publik.
Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 membuka ruang yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam hukum dan pemerintahan. Bahkan, negara mengakui pentingnya affirmative action melalui kebijakan kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam politik. Namun realitas menunjukkan, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuasaan yang nyata di ruang-ruang strategis.
Hambatan keterlibatan perempuan dalam politik bersifat kompleks dan berlapis. Budaya patriarki masih menempatkan politik sebagai ranah maskulin, sementara perempuan direduksi pada peran domestik dan dilekati stigma emosional serta kurang tegas. Di sisi lain, struktur partai politik yang tidak ramah perempuan, mahalnya biaya politik, keterbatasan akses jejaring elite, hingga ancaman kekerasan verbal, seksual, dan digital menjadikan politik sebagai ruang yang tidak aman. Beban peran ganda antara tanggung jawab domestik dan kerja publik kian mempersempit ruang gerak perempuan untuk berpolitik secara optimal.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 menjadi titik penting dalam perjuangan representasi perempuan. MK menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di alat kelengkapan dewan tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus proporsional dan merata di setiap fraksi dan lembaga. Putusan ini menandai pergeseran paradigma: dari sekadar “hadir” menuju “berpengaruh”. Sebab kehadiran tanpa kuasa hanya akan melanggengkan ketimpangan dalam wajah baru.
Data representasi perempuan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan paradoks demokrasi. Perempuan secara kuantitas cukup dominan di sektor birokrasi, namun minim di posisi pengambil kebijakan strategis. Padahal berbagai kajian menunjukkan bahwa perempuan membawa perspektif berbeda dalam merumuskan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan isu kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan generasi.
Di sinilah relevansi peran KOHATI menjadi krusial. Sebagai Korps HMI-Wati, KOHATI tidak sekadar mencetak kader perempuan yang aktif secara organisatoris, tetapi membentuk insan akademis, pencipta, pengabdi, dan bertanggung jawab yang bernapaskan Islam. Politik dalam pandangan kader HMI-Wati bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan medan pengabdian ideologis untuk menghadirkan keadilan dan kemanusiaan. Ideologi memberi arah moral, politik menyediakan arena, strategi memetakan jalan, dan taktik mengeksekusi perubahan.
Dalam QS. Ar-Ra’d ayat 11 mengingatkan bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa kesadaran dan ikhtiar dari diri sendiri. Maka keterlibatan perempuan dalam politik adalah bagian dari tanggung jawab sejarah untuk mengubah kondisi ketimpangan menjadi keadilan, dari representasi simbolik menuju kekuasaan yang membebaskan.
Sudah saatnya perempuan tidak hanya dihitung, tetapi didengar. Tidak hanya dihadirkan, tetapi dilibatkan. Dan tidak hanya ditempatkan, tetapi dikuatkan.
Demokrasi yang berkeadaban hanya mungkin lahir ketika perempuan hadir sebagai subjek politik sepenuhnya, bukan sekadar pelengkap statistik.
Yakin Usaha Sampai.